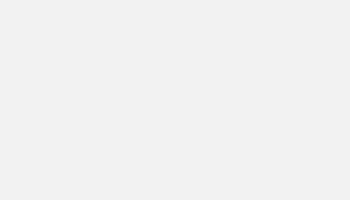Bandung, kota yang terkenal dengan udaranya yang sejuk, menawarkan pengalaman sarapan pagi yang tak terpisahkan dari semangkuk bubur ayam hangat. Di sudut kawasan Bandung Timur, di tengah keriuhan pasar kecil, terdapat kisah hangat yang terajut dari keuletan Mang Opik, seorang penjual bubur yang telah mengabdikan diri selama belasan tahun.
Baca Juga : Wakil Presiden Gibran Gantikan Presiden Prabowo Hadiri KTT G20 Afrika Selatan
Aroma Pagi di Tengah Pasar
Pagi di Bandung Timur masih diselimuti kabut tipis. Jalanan sempit, yang lembab karena sisa hujan semalam, mulai dipadati oleh hiruk pikuk aktivitas. Di sana-sini terlihat pedagang sayur menata dagangan, tukang kue menjajakan santapan manis, dan deretan sepeda motor yang berhenti sejenak untuk mengambil porsi sarapan.
Di antara keramaian itu, berdirilah gerobak berwarna cokelat muda dengan stiker bertuliskan “Bubur Ayam Pasor” yang telah usang. Dari gerobak inilah uap panas perlahan naik, membawa aroma kaldu ayam yang gurih, berpadu dengan wangi bawang goreng yang baru diangkat dari minyak panas.
Mang Opik, lelaki paruh baya asal Majalengka, telah siap melayani pelanggan sejak menjelang subuh. Tangannya bergerak cekatan mengaduk bubur di dalam panci besar. Gerak tubuhnya menunjukkan sebuah rutinitas yang telah terbentuk dari pengalaman bertahun-tahun.
“Sudah lima belas tahun di sini, dari dulu ya di gerobak ini juga,” katanya pelan, mengisahkan kesetiaannya pada lokasi dan gerobak yang sama.
Filosofi “Pasor” dan Konsistensi Rasa
Nama “Pasor” ternyata merupakan singkatan sederhana dari “pagi-sore”. Dulu, Mang Opik memang berjualan dari pagi hingga petang. Namun, kini ia memilih fokus melayani sarapan pagi saja, meskipun nama itu tetap dipertahankan sebagai pengingat masa-masa awal merintis.
Ia bercerita bahwa masa-masa awal berdagang sering kali diliputi sepi pembeli. Bubur kerap tak habis hingga siang hari. Meski begitu, ia tetap bertahan. “Kalau sepi, ya dijalani, namanya juga jualan,” ujarnya dengan nada tenang.
Gerobaknya kecil, namun tertata rapi. Di sisi kiri, sate pendamping — seperti sate usus, ati ampela, dan telur puyuh — tersusun rapi menggugah selera. Di sisi kanan, toples-toples berisi kacang, bawang goreng, dan kerupuk disiapkan dengan teratur.
Fokus utamanya adalah pada panci besar berisi bubur. Ia tak pernah membiarkan bubur mengental tanpa pengawasan. Ia sering mengaduknya perlahan, bahkan saat belum ada pembeli.
“Kalau lagi masak, bubur nggak boleh ditinggal. Apinya pun harus pas, benar-benar harus teliti,” jelasnya, menekankan pentingnya perhatian penuh dalam proses memasak.
Bubur racikannya terkenal karena kesederhanaan rasanya yang mantap. Disajikan tanpa kuah terpisah, kelembutan bubur yang gurih berpadu sempurna dengan suwiran ayam, potongan cakwe renyah, dan sambal merah sebagai penambah selera.
Banyak pelanggan justru menganggap sate pendamping sebagai primadona. Sate-sate Mang Opik memiliki cita rasa khas asin, manis, dengan sentuhan gosong yang unik di bagian tepinya. “Satenya memang paling cepat habis, kadang sebelum jam delapan udah ludes,” katanya sambil tersenyum kecil.
Menakar Rezeki dan Kesabaran
Mang Opik mengaku tidak memiliki resep rahasia atau warisan khusus. Semua racikannya ia ciptakan sendiri, lahir dari pengalaman dan serangkaian percobaan yang tidak terhitung. Namun, satu hal yang selalu ia jaga adalah kesabaran.
Baginya, membuat bubur ayam dan menghadapi hari-hari berdagang membutuhkan napas panjang. Ketekunan dan kesabaran ini, ia akui, berakar dari tanggung jawab untuk menafkahi anak dan istrinya. Kebutuhan keluarga menjadi penyemangat utama yang membuatnya tetap bersemangat di gerobaknya setiap pagi.
Bagi sebagian orang, gerobak bubur Mang Opik mungkin hanya pemandangan biasa di pinggir jalan. Namun, bagi dirinya, di sanalah seluruh kehidupannya berputar; tempat ia menakar rezeki, menakar rasa, dan menakar kesabaran, menjadikannya sebuah ritual yang dijalani dengan konsisten setiap hari.
Sebelum matahari sepenuhnya terbit, ia sudah menyiapkan semua. Tangan tuanya cekatan mengaduk dan mencampur, menghasilkan uap panas dan aroma gurih yang menembus dinginnya udara pagi. Setiap sendok bubur yang ia tuangkan adalah representasi dari ketekunan. Kadang, di sela waktu lengang, ia duduk sejenak menyeruput teh hangat, mengamati lalu lintas orang-orang yang bergegas mengejar waktu.
“Hidup memang seperti bubur,” katanya sambil tersenyum tipis, “harus sabar diaduk biar rasanya pas.”